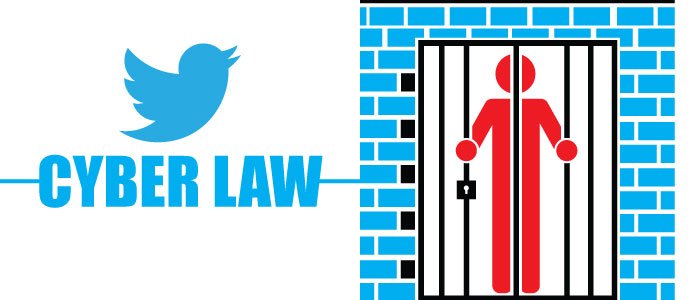Para pembaca mungkin sudah familiar dengan kasus Florence Sihombing. Mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Jogjakarta ini harus terlibat dalam ranah hukum yang berkaitan dengan UU ITE (peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik) di Indonesia. Peraturan tersebut – yang dibuat pada tahun 2008 – mengatur aktivitas online warga negara, dan memungkinkan siapa saja menuntut orang yang membuat mereka “merasa tersinggung”.
Indonesia adalah negara demokrasi dengan amandemen konstitusi yang menjamin kebebasan berekspresi. Namun kenyataannya, keberadaan UU ITE bertentangan dengan amandemen tersebut.
Kasus Florence Sihombing adalah salah satu dari banyak insiden yang menunjukkan bagaimana UU ITE mempunyai banyak interpretasi. Kami juga akan melihat kasus-kasus lain yang berkaitan dengan UU ITE yang menunjukkan kurangnya pemahaman para penegak hukum ketika berhadapan dengan isu-isu seperti ini.
Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari kita lihat beberapa kasus terakhir.
Kasus Florence Sihombing
Florence mengatakan bahwa orang Jogjakarta “miskin, tolol, dan tak berbudaya” di jejaring sosial Path. Seseorang lalu mengambil screenshot statusnya dan menyebarkannya ke media sosial. Para netizen yang tidak terima dengan status Florence tersebut, mem-bully-nya di media sosial. Di Twitter, #UsirFlorenceDariJogja menjadi hashtag yang trending.
Situasi semakin memburuk ketika sebuah LSM lokal secara resmi melaporkan Florence ke pihak kepolisian dengan dasar UU ITE. Mereka menilai bahwa Florence bersalah karena melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, dan provokasi mengkampanyekan kebencian. Florence akhirnya meminta maaf secara publik. Dan meskipun beberapa LSM mengatakan bahwa mereka memaafkannya, mereka masih ingin melanjutkan proses hukum.
Insiden yang sama juga terjadi di Bandung belakangan ini. Walikota Bandung Ridwan Kamil melaporkan pengguna Twitter Kemal Septiandi. Kemal dianggap menghina Bandung dan Ridwan Kamil di Twitter dengan kata-kata yang tidak mengenakkan. Tapi apakah tindakan online yang dilakukan Florence dan Kemal (salah satunya sebenarnya bersifat pribadi) membuat mereka layak dicap sebagai penjahat?
Masalah lainnya
Southeast Asia Freedom of Expression (SafeNet), sebuah gerakan yang mempromosikan kebebasan berbicara di Asia Tenggara, telah mengkaji UU ITE di Indonesia. Meskipun mereka percaya UU ITE diperlukan untuk mengatur aktivitas online, UU tersebut memiliki beberapa celah yang harus diperbaiki.
1. Tidak jelas apakah pelanggaran UU ITE masuk dalam hukum perdata atau pidana
Karena pencemaran nama baik bisa menjadi kasus perdata dan pidana di Indonesia, pemerintah perlu memperjelas hal ini. Australia, misalnya, mengatur bahwa setiap kasus pencemaran nama baik yang merugikan individu harus dianggap sebagai pelanggaran perdata. Saat insiden bisa mempengaruhi masyarakat, seperti membahayakan keamanan publik, maka dapat dianggap sebagai tindak pidana. Karena parameternya belum didefinisikan secara jelas di Indonesia, ada beberapa insiden kecil yang harusnya masuk dalam kasus perdata bukan kasus pidana.
Salah satunya adalah insiden pada tahun 2010 yang melibatkan dua siswa SMA yang mengina satu sama lain di Facebook. Pada akhirnya salah satu dari mereka mengajukan gugatan, dan berhasil membuat siswa lainnya divonis bersalah. Siswa tersebut akhirnya dihukum dua bulan dan 15 hari penjara, tapi tidak harus menjalani hukuman kurungan apabila tidak melanggar hukum selama lima bulan.
2. Penegak hukum tidak sepenuhnya memahami cara penanganan kasus pencemaran
Ada satu kasus tentang Donny Iswandono, wartawan yang dituntut dengan UU ITE karena menulis artikel tentang korupsi di Kabupaten Nias Selatan. Donny mengklaim telah mengikuti etika jurnalistik dengan meminta komentar Bupati sebelum menerbitkan artikel itu, tapi diabaikan. Indonesia Corruption Watch (ICW) percaya bahwa polisi seharusnya memprioritaskan penyidikan kasus terhadap korupsi Bupati dibanding tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan Donny.
Koordinator regional SafeNet Voice Damar Juniarto mengutip kasus Benny Handoko, yang dinyatakan bersalah telah melakukan pencemaran nama baik melalui tweet-nya. Damar mengatakan bahwa hakim tidak mengikuti protokol umum untuk mengevaluasi bukti forensik digital yang diperlukan untuk mengetahui “niat” dalam memfitnah orang. Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki niatan atau tidak, pelaku harus terbukti mencemarkan nama baik seseorang lebih dari sekali. Hakim mengabaikan digital forensik yang diajukan oleh pengacara pembela. Selain itu, melaporkan seseorang ke polisi juga sangat mudah. Seringkali, satu SMS saja sudah cukup, seperti apa yang terjadi pada kasus Muhammad Arsad yang masih berlangsung, yang mengirim SMS ke atasannya, Bupati Kepulauan Selayar.
Polisi memiliki kewenangan untuk menahan orang yang dihukum dalam tahanan selama 20 hari setelah gugatan didaftarkan. Jadi mereka harus benar-benar yakin apakah penahanan benar-benar masuk akal sebelum melakukannya.
3. Hukuman tidak selalu sesuai Damar mengutip dua contoh terbaru yakni Florence Sihombing dan Kemal
Keduanya merupakan kasus dimana jaksa ingin menegakkan etika internet baik dalam masyarakat. Ia percaya bahwa jika pemerintah ingin mendidik netizen tentang etika online, maka mereka harus mengajarkan masyarakat tentang itu. Pendidikan merupakan pendekatan yang lebih langsung daripada memasukkan seseorang di penjara. “Saya pikir mereka tidak akan belajar banyak tentang etika dalam penjara,” katanya.
4. Pemerintah harus lebih konsisten menginvestigasi kasus-kasus yang lebih serius di Indonesia
Pemilihan presiden yang lalu memunculkan banyak kampanye hitam yang menargetkan calon presiden. Di sinilah UU ITE tentang pencemaran nama baik bisa memainkan peran besar. Namun kenyataannya, tidak ada penangkapan yang terjadi.
Hukuman yang tidak proporsional dan kebebasan berekspresi
UU ITE juga dianggap menerapkan hukuman yang tidak proporsional untuk kasus pencemaran nama baik jika dibandingkan dengan kasus pidana ringan. Mereka yang terbukti bersalah di bawah hukum pidana, misalnya, dapat dihukum sampai sembilan bulan penjara atau denda hingga Rp 4.500. UU ITE memberikan hukuman hingga enam tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 1 miliar. Pelapor khusus kebebasan berekspresi PBB Frank La Rue mengatakan bahwa pencemaran nama baik secara online harusnya memiliki hukuman yang lebih ringan bila dibandingkan dengan kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media cetak. Karena dalam kasus online, individu yang bersangkutan bisa segera “menggunakan haknya untuk membalas langsung guna menanggulangi kerugian yang terjadi.”
Selain itu, ada juga beberapa bagian dalam UU ITE yang mempunyai banyak interpretasi. UU ITE memungkinkan Anda menuntut seseorang yang membuat Anda merasa “tersinggung”, “takut”, atau “terprovokasi”. Tentu UU ini sangat subjektif. Seseorang mungkin merasa terhina hanya dengan membaca status media sosial yang di-posting oleh seseorang yang mereka tidak tahu, sementara seseorang yang lainnya mungkin hanya akan mengabaikannya. Beberapa orang berpendapat bahwa karena UU ITE mengatur sengketa antara individu, maka mungkin lebih tepat memasukkannya pada hukum perdata daripada pidana. Badan internasional seperti PBB dan Organization for Security and Co-operation di Eropa juga menyerukan dekriminalisasi pencemaran nama baik karena membatasi kebebasan berekspresi.
Apakah bisa direvisi?
Apakah ada harapan untuk merevisi UU ITE? Mungkin. Damar mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan empat review tentang UU ITE, namun tidak satupun yang berujung pada perubahan regulasi. Menurut Damar, melakukan review lagi tidak akan ada gunanya. Satu-satunya harapan terletak pada Kemkominfo, yang tiga minggu lalu berjanji kepada SafeNet bahwa mereka akan merevisi UU. Tapi Damar sedikit skeptis, karena janji yang sama juga dibuat dua tahun lalu dan tanpa hasil apapun.
Sejak UU ITE diberlakukan, ada lebih dari 50 kasus tentang hal ini yang menjadi sorotan. SafeNet berharap Menteri Kominfo yang baru akan membuat kebijakan yang berbeda. Untuk saat ini, pemerintah harus mendidik warga tentang penanganan kasus pencemaran nama baik secara online. Dan meskipun pencemaran nama baik dianggap sebagai tindak pidana di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia, kasus tersebut lebih sering diperdebatkan dalam hukum perdata.
Vietnam adalah negara Asia lain yang mungkin memiliki undang-undang internet yang sama atau bahkan lebih ketat. Negara bisa memenjarakan siapa saja yang aktivitas online-nya dianggap “bertentangan dengan kepentingan negara.”
Sumber: Techinasia.com